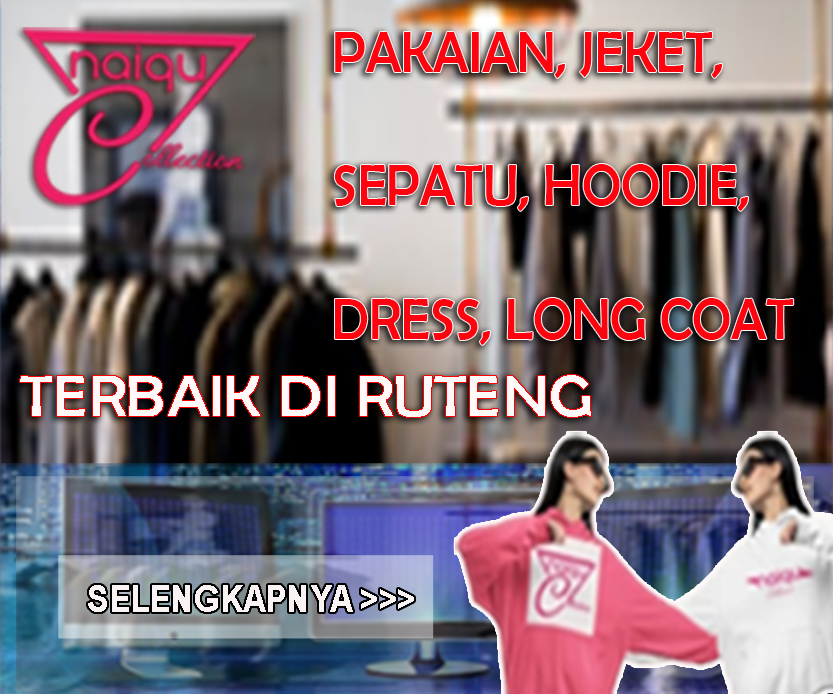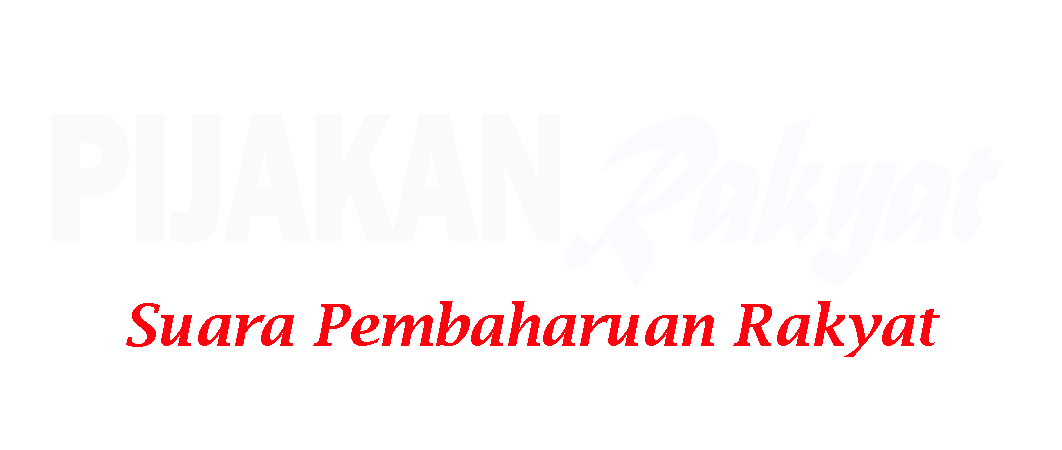Menelisik Kartini dari Paskah: Refleksi tentang Perempuan Indonesia Dewasa Ini
 |
| Foto: Fransiskus Jemadi (Sumber: dok. Pribadi) |
Penulis: Fransiskus Jemadi
Dosen pada Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
Jika kita menyatukan semangat Kartini dan makna Paskah, lahirlah sebuah refleksi yang sangat relevan dengan kondisi perempuan Indonesia masa kini.
PIJAKAN rakyat- April kali ini sunnguh berbeda. Kita memperingati dua momen penting yang bersisian dalam kalender: Hari Raya Paskah dan Hari Kartini. Keduanya berasal dari tradisi yang berbeda— satu dari tradisi iman, satu dari sejarah bangsa. Namun, keduanya menawarkan semangat yang serupa: keberanian menghadapi penderitaan, harapan atas perubahan, dan semangat kebangkitan.
Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai pelopor emansipasi perempuan di Indonesia. Melalui surat-suratnya yang ditulis dalam kesunyian hidupnya, Kartini menyuarakan pemikiran yang jauh melampaui zamannya. Ia tidak hanya menginginkan akses perempuan terhadap pendidikan, tetapi juga menuntut perubahan cara pandang masyarakat terhadap martabat dan potensi perempuan. Kartini percaya, peradaban akan lumpuh jika perempuan terus-menerus dibungkam.
Paskah, di sisi lain, merupakan tonggak keimanan yang mengandung makna kebangkitan dari penderitaan. Dalam tradisi iman Kristiani, Paskah merayakan kemenangan hidup atas kematian, terang atas kegelapan. Nilai ini tidak hanya berlaku dalam ranah spiritual, tetapi juga dapat menjadi lensa reflektif dalam melihat realitas sosial. Seperti halnya Kartini yang percaya bahwa cahaya akan datang setelah gelap, Paskah meneguhkan harapan bahwa dari kehancuran pun, kehidupan baru bisa lahir.
Jadi, Jika kita menyatukan semangat Kartini dan makna Paskah, lahirlah sebuah refleksi yang sangat relevan dengan kondisi perempuan Indonesia masa kini.
Emansipasi yang Belum Paripurna
Emansipasi perempuan bukan sekadar kisah masa lalu. Ia adalah perjuangan yang terus berlangsung dalam berbagai bentuk. Kartini memang telah membuka jalan, namun jalan itu belum sepenuhnya dilalui. Dalam banyak kasus, perempuan Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang membuat mereka berjalan lebih lambat dibanding laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan.
Hingga hari ini, diskriminasi berbasis gender masih kerap terjadi—baik secara terang-terangan maupun dalam bentuk yang lebih halus. Perempuan sering kali harus membuktikan kompetensinya dua kali lebih keras. Mereka juga dibebani ekspektasi ganda: sukses di dunia kerja, namun tetap mengemban seluruh tanggung jawab domestik. Ini adalah realitas yang belum banyak berubah, bahkan ketika pendidikan dan partisipasi publik perempuan meningkat.
Dalam ruang-ruang sosial dan budaya yang masih menyisakan bias patriarkal, perempuan kadang harus memilih: antara suara dan keselamatan, antara karier dan keluarga, antara ekspresi diri dan penerimaan sosial. Ini bukanlah pilihan yang adil. Dan justru di sinilah kita melihat bahwa semangat Kartini masih sangat dibutuhkan—bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dilanjutkan.
Paskah: Simbol Kebangkitan Perempuan
Di tengah kenyataan yang tidak selalu berpihak, perempuan Indonesia menunjukkan daya tahan luar biasa. Mereka adalah representasi nyata dari semangat Paskah: bangkit dalam kesenyapan. Banyak dari mereka yang mengalami kekerasan, ketidakadilan, atau ketimpangan akses, namun memilih untuk bertahan dan membangun kembali kehidupan mereka.
Kisah-kisah kebangkitan ini sering luput dari sorotan. Seorang ibu tunggal yang bekerja siang malam demi pendidikan anaknya. Seorang guru honorer di daerah terpencil yang tetap mengajar meski gajinya jauh dari layak. Seorang perempuan kepala desa yang berjuang melawan budaya patriarkal agar warganya mendapatkan akses air bersih. Mereka adalah wajah-wajah Paskah dalam kehidupan sehari-hari—tidak bersuara keras, tapi mengubah dunia dengan keteguhan hati.
Perempuan dan Masa Depan Bangsa
Kemajuan perempuan Indonesia dalam pendidikan, ekonomi, dan politik memang patut diapresiasi. Namun, kemajuan itu tidak boleh membuat kita abai terhadap fakta bahwa kesetaraan belum merata. Masih banyak perempuan di pelosok negeri yang belum mendapat akses pendidikan, pelayanan kesehatan reproduksi yang memadai, ataupun perlindungan hukum yang adil.
Kebijakan afirmatif dan program pemberdayaan perlu terus diperkuat, bukan sekadar dalam angka statistik, tapi dalam dampak nyata yang dirasakan perempuan di tingkat akar rumput. Kesetaraan bukan hanya tentang posisi, tetapi tentang nilai: bagaimana perempuan dihargai, dilibatkan, dan dilindungi dalam setiap aspek pembangunan bangsa.
Refleksi yang Mendesak
Ketika kita menelisik Kartini dari Paskah, kita sesungguhnya sedang diajak untuk meninjau kembali arah gerak bangsa ini. Apakah kita sungguh-sungguh sedang membangun masyarakat yang adil gender? Ataukah kita masih melanggengkan sistem yang meminggirkan perempuan secara sistemik?
Kartini tidak sedang menunggu kita mengenangnya dengan pidato atau perayaan simbolik. Ia menanti aksi nyata. Begitu pula Paskah: bukan hanya seremoni, tetapi seruan untuk bangkit. Bangkit dari bias, dari kebungkaman, dari ketidakadilan yang dibenarkan atas nama tradisi.
Menutup refleksi ini, saya ingin mengajak kita semua berhenti sejenak dan benar-benar merasakan apa artinya menjadi perempuan di negeri ini. Perempuan yang terus berdiri, bahkan ketika dipaksa berlutut oleh norma yang tak adil. Perempuan yang tersenyum, bahkan ketika haknya dipangkas tanpa suara. Perempuan yang, seperti kisah Paskah, memilih untuk bangkit dari luka, dari ketidakadilan, dari sunyi yang panjang—demi masa depan yang lebih layak.
Perempuan tidak butuh belas kasihan. Mereka hanya butuh dipercaya. Diberi ruang untuk menjadi diri mereka sendiri—utuh, kuat, dihormati. Ketika perempuan bangkit, itu bukan sekadar kemenangan pribadi. Itu adalah kabar suka cita bagi kita semua. Sebab saat perempuan benar-benar berdiri, bangsa ini tidak hanya berjalan. Ia melompat lebih jauh—dengan cinta yang lebih besar, dan harapan yang lebih utuh. Ia bergerak menuju transformasi yang sejati. (Redaksi PR)